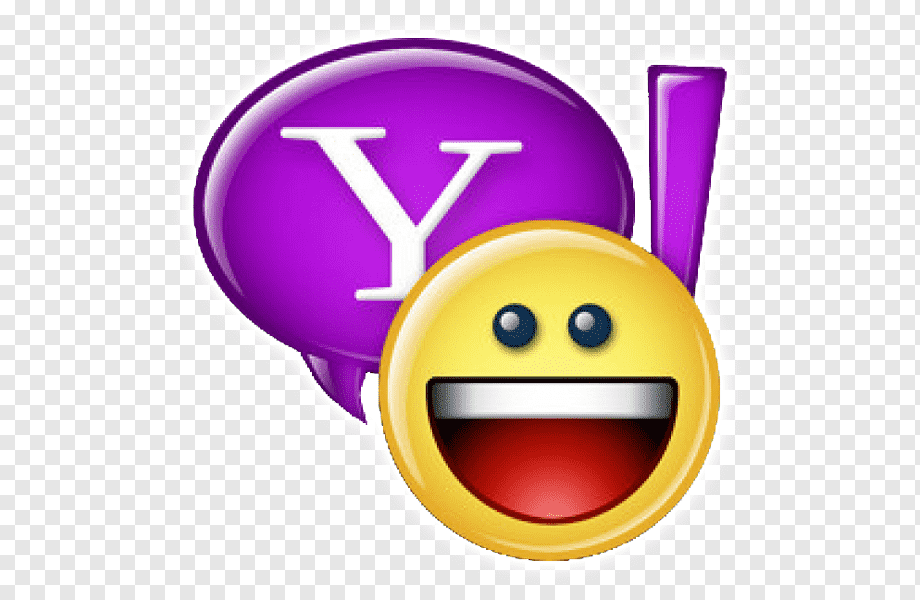Ekonomi Pancasila Berwajah Syariah?
- Written by Super User
- Category: Kolom Ketua
Setiap bulan Juni dikenal sebagai bulan Pancasila. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila telah dijadikan dasar dan falsafah hidup. Pancasila lahir 1 Juni 1945, dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama UUD 1945. Maka, sebagai common sense, apapun yang hendak dikembangkan di Tanah Air, sejatinya merujuk pada falsafah Pancasila.
Di sudut lain, ajaran Islam, yang memiliki sistem dan tatanan hidup dengan prinsip universalisme dan kosmopolitanisme, senantiasa memandang, apapun falsafah hidup yang bergerak di tengah masyarakat, asalkan berada pada prinsip universalisme dan kosmopolitanisme Islam, tentu akan kompatibel (Madjid, 1992). Sangat tepat jika disebutkan, ekonomi Pancasila, yang memiliki nilai-nilai universal dan berlandaskan maqasid syariah, yakni memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku.
Untuk menegaskan hal itu, rumusan universalitas dasar ekonomi syariah, yakni, pertama, bertujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera. Kedua, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama serta yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. Ketiga, dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. Keempat, dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin. Kelima, pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. Keenam, perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. Ketujuh, hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal (Karim, 2003, Chapra, 2001).
Beranjak pada falsafah ekonomi syariah dan Pancasila itu, kompatibilitas dalam gerakan dan perjuangan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di Tanah Air, sudah tidak bisa lagi dipertentangkan. Pelbagai macam kebijakan dan perilaku ekonomi yang mencampakkan rasa keadilan sosial, harus dilawan. Penindasan, eksploitasi, diskriminasi, favoritisme, dan eksklusivisme dalam hidup berekonomi, menjadi musuh dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.
Ekonomi Pancasila
Mengingat kompatibilitas itu, dalam merumuskan dasar ekonomi Negara, Bung Hatta (1975) menggagas “...Ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing seperti yang dikemukakan pertama kali oleh Bung Karno, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya.”
Selanjutnya Hatta (1980) mengatakan: “...dasar yang memimpin bagaimana hendaknya hidup kita dalam masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kelanjutan daripada sila kesatu tadi, yang mengakui dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia hendaklah kita pelihara baik-baik. Sila keempat ialah supaya kita menjalankan demokrasi kerakyatan yang didasarkan kepada hikmah kebijaksanaan dan musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat. Musyawarah itu penting karena demokrasi ada hubungannya dengan musyawarah. Demokrasi harus berdasarkan musyawarah, musyawarah dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang membawa kepercayaan rakyat ke sana. Kemudian sila kelima ialah sila keadilan sosial. Kalau kita menerima sila keadilan sosial ini sebagai bagian dari Pancasila, maka hendaklah dipraktikkan.”
Dengan proposi itu, kian jelas bahwa kepatuhan dan komitmen pada falsafah Pancasila, merupakan suatu neccesery condition, karena posisi Pancasila “mengikat seluruh lapisan masyarakat, terutama mengikat pemerintah dan instrumen-instrumen negara yang bertugas sebagai eksekutor”. Dalam konteks itulah, sungguh tepat, jika ingin terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kemerosotan moral dan akidah, serta ketertindasan, teologi Surat Al-Ma’un ayat 1-7 menjadi pijak yang kompatibel dengan spirit ekonomi Pancasila.
Dalam pasal 33 UUD 1945, terang benderang menyebutkan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.“
Paralel hal itu, Rasulullah SAW menukil: “almuslimuna syuroka’u fi tsalatsatin, fil ma’i, wal kalai wan nari” (orang-orang Islam bersyarikat dalam tiga hal: air, rumput (pangan), dan api. (HR Abu Daud). Hadits ini mendeskrpsikan, komoditas publik (air, pangan, dan energi) adalah hak milik bersama dan menjadi kewajiban negara untuk “menguasai”, melindungi, mengawasi dan mengoptimalisasikannya untuk kesejahteraan rakyat.
Menyusun Ekonomi
Dengan dasar itu, sejatinya kebijakan ekonomi harus “disusun” sesuai makna demokrasi ekonomi. Secara imperatif, Negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar kebersamaan dan kekeluargaan. Karena itu, sangat tepat jika “ketersusunan” ekonomi tidak diserahkan pada liberalisme pasar yang rakus, yang melahirkan penindasan, eksploitasi, dan penghancuran alam, tapi harus sengaja di desain. Dalam QS al-Hasyir ayat 7, Allah memberi ruang kepada manusia untuk menyusun dan mendesain model terciptanya pemerataan distribusi pendapatan.
Demikian juga, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (at-ta’wun) beradasarkan atas asas kekeluargaan dan kerjasama (syirkah). Tentu, instrumen operasionalnya, adalah koperasi. Koperasi, menurut Bung Hatta, memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling kerjasama. Hatta menginginkan agar dalam koperasi, mereka yang miskin harus dibela dan diberi kesempatan. Tentu, hal ini sejurus QS. al Ma’un: 1-3; “pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau membela dan memberi makan orang miskin”.
Dalam konteks keterlibatan negara, spirit ekonomi Pancasila menegaskan, untuk menguatkan potensi ekonomi rakyat, negara tidak boleh absen dalam kerakusan free fight liberalism. Rakyat harus diberi kesempatan dalam demokrasi ekonomi, yakni kesempatan partisipasi dan emansipasi. Dalam demokrasi ekonomi, semua bisa duduk bersama. Oleh karena itu, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus simultan.
Jika demokrasi politik dilepas, tanpa demokrasi ekonomi, yakinlah akan melahirkan “petaka” kerakusan individualisme. Kasus gurita keberadaan koporasi multinasional dan pemodal kakap, yang kian menancapkan kukunya, menghisap kekayaan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja kita, sebagai bukti abainya Negara dalam menyusun demokrasi politik, tanpa demokrasi ekonomi. Tentu hal ini, paralel dengan prinsip musyawarah (Qs 3: 159) dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik (al-makrufat) dan lebih maslahat (al-mashlahat) bagi rakyat luas.
Dalam kaitan jaminan sosial, pasal 34 UUD 1945 disebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ekonomi Pancasila memandang, masalah kemiskinan tidak saja terkait dengan masalah ekonomi, tapi juga terkait dengan kehidupan keagamaan seseorang. Kata Bung Hatta: “Jangan dikira orang miskin yang begitu banyak, hidup meminta-minta akan taat beragama. Mereka malahan menyumpah-nyumpah, mengapa Tuhan menjadikan nasibnya begitu jelek”. Tentu, hal ini sangat sejalan dengan hadis Nabi: “hampir-hampir kefakiran itu membuat orang menjadi kufur”. Dan instrumen yang tepat, negara harus memaksa kewajiban zakat.
Demikian juga ihwal penataan pertanahan (landreform). Dalam perspektif ekonomi Pancasila, landreform penting karena tanah adalah faktor produksi penting, alat menghasilkan. Ini artinya, baik buruknya penghidupan rakyat tergantung kepada keadaan milik tanah. Perspektif ini tentu sesuai spirit Islam, tanah dituntut untuk dikelola dan diproduktifkan bagi yang memilikinya agar tercipta kesejahteraan di tengah masyarakat.
Namun, menjadi illat bagi pencabutan dan pengalihan kepemilikan serta pengolahan tanah tersebut dalam Islam bukanlah masalah luas tanah yang dimiliki seseorang, tetapi “karena tanah tersebut dibiarkan, tidak dikelola”. Abbas (2010) secara gagah mengupas dialog Umar bin Khattab dengan Bilal, seperti dinukil Taqyuddin an Nabhani, Umar berkata kepada Bilal; “..bahwa Rasulullah saw tidak akan memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka ambillah dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola dan yang lain (yang tidak bisa kamu kelola) kamu kembalikan”.
Dengan konstatasi itu, tidak ada alasan lagi, jika kita masih mempertentangkan ekonomi syariah dengan Pancasila. Bahkan, jika ekonomi syariah hendak digerakkan secara masif, tidak perlu ragu menggunakan “jubah” ekonomi Pancasila. Kompatibilitas menjadi keniscayaan, karena kita yakin, bahwa ekonomi syariah memiliki nilai-nilai universalitas yang abadi.