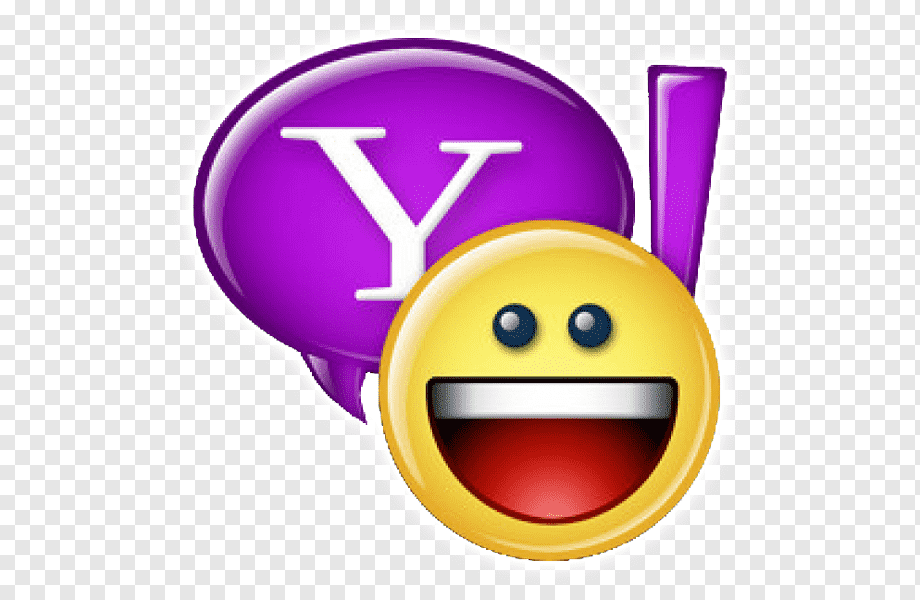Terorisme Ekonomi
- Written by titotito
- Category: Kolom Ketua
Oleh: Mukhaer Pakkanna
(Rektor STIE Ahmad Dahlan Jakarta)
Serangkaian aksi teror yang meruyak akhir-akhir ini, kemudian menyusul aksi teror yang menewaskan 7 (tujuh) orang di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, pada medio Januari 2016, mengirimkan pesan bahwa aksi teror seperti itu harus dibasmi. Aksi teror telah melumatkan banyak manusia yang tidak berdosa dan memberi efek sosio-psiokologis, yakni menebar rasa takut. Rasa takut inilah yang kerap memproduksi frustrasi, takut dan rasa tertekan.
Sejatinya, rasa takut kerapkali tidak serta merta menerima dengan pasrah terhadap kejadian teror tersebut. Ada sisi “bawah sadar” dalam diri seseorang untuk berusaha melawan kejadian itu dengan sekuat tenaga (Wijaya, 2001). Namun, upaya perlawanan tidak mampu diaktualisasikan secara konkret karena ketidakberdayaan dirinya. Dan, ketikberdayaan itulah yang banyak dirasakan oleh rakyat dalam pelbagai jenis teror yang dihadapinya.
Terorisme ekonomi adalah salah satu jenis teror yang kerap menyelimuti ekonomi rakyat. Rakyat menjadi tidak berdaya karena menghadapi problema struktural, yang ujungnya melahirkan ketimpangan dan kesenjangan. Mengonfirmasi Joseph E Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality (2005), ketimpangan dan kesenjangan terutama dalam aset dan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan politik, ketimbang konsekuensi dari bekerjanya kekuatan pasar (makro ekonomi). Artinya, ketimpangan dan kesenjangan adalah buah dari kebijakan pemerintah sendiri.
Gerakan terorisme apapun jenisnya, adalah produk ketidakadilan struktural. Dalam bidang ekonomi, ketidakadilan dapat dilihat kasat mata berupa ketimpangan itu. Lemahnya pemihakan negara kepada ekonomi rakyat, yang diiringi pemberian privilege (keistimewaan khusus) bagi kelompok tertentu, terutama kepada kuasa kapital yang di-back-up oleh oligarki politik, memberi “karpet merah” kepada kuasa kapital menguasai sumberdaya-sumberdaya ekonomi. Dalam konteks itulah, kuasa kapital melakukan siasat “teror mental” (Andalas, 2010), sehingga memicu ekonomi rakyat tidak berdaya.
Ketidakberdayaan
Implikasi ketidakberdayaan ekonomi rakyat telah melahirkan pelbagai fakta miris. Pertama, mengacu data Credit Suisse, Bank Dunia (2014) mencatat, 1 (satu) persen orang terkaya menguasai separoh lebih kekayaan Indonesia, besarannya mencapai 50,3 persen. Besaran itu, bukan hanya aset uang, melainkan juga properti. Jika pada 2002, sekitar 10 persen warga terkaya tercatat mengonsumsi sama banyaknya dengan toral konsumsi 42 persen warga termiskin, maka pada 2014 tercatat ada 10 persen orang terkaya mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin.
Penguasaan kekayaan seperti itu menjadi fakta Koefisien Gini yang kian terdongkrak dari 30 poin pada 2000 menjadi 41 pada 2014. Ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Koefisien Gini Indonesia ini berposisi sama dengan negara miskin lain, Uganda dan Pantai Gading. Tingkat ketimpangan ini justru melaju paling cepat di antara negara-negara tetangga di Asia Timur. Padahal, beberapa negara jiran, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand mencatatkan penurunan angka Koefisien Gini.
Menurut Bank Dunia, negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi berpotensi mengalami konflik 1,6 kali lebih besar. Sebab, adanya perbedaan pendapatan dan pelayanan antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga akan menggerus perekonomian.
Kedua, laporan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2015, mencatat ada 216.762 rekening di bank di Indonesia yang memiliki nilai simpanan di atas Rp 2 milyar. Sesuai ketentuan, nilai nominal simpanan masyarakat yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maksimal Rp 2 miliar per rekening. Data itu setidaknya menunjukkan, gambaran ketimpangan secara kasat mata, antara mereka yang tidak mampu membayar biaya sekolah dengan mereka yang berkelebihan.
Ketiga, ketimpangan penguasaan lahan. Berdasarkan data BPN (2014), ketimpangan lahan saat ini berada dikisaran 0,64 (Gini Ratio). Sekitar 70% asset ekonomi berupa tanah, tambak, kebun, dan property di Negara ini hanya dikuasi oleh 0,2% penduduk.
Keempat, dalam bidang penguasaan jaringan retail, jenis usaha besar telah menguasai dan membunuh warung-warung kelontong rakyat. Menurut analisis Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPTI), keberadaan minimarket modern dianggap telah menyedot pembeli yang selama ini biasa belanja di warung tradisional. Setiap pendirian 1 (satu) minimarket, maka akan meneror (membunuh) sekitar 20 (dua puluh) pedagang tradisional. Indomaret dan Alfamart yang selalu setia bersaing sampai kepelosok desa, keberadaannya lambat laun akan membunuh pedagang tradisional.
Dalam faktanya, di pasar-pasar moderen, baik sekelas mini, super, maupun hypermarket, kerapkali produk dipromosikan secara berlebihan dengan pelbagai tawaran diskon tinggi. Dalam strategi bisnis, praktik seperti ini disebut predatory pricing atau mengambil risiko merugi beberapa waktu untuk meneror pesaing yang bermodal kecil (biasa disebut juga sebagai wal-mart effect). Akibatnya, pembeli lebih senang membelinya di pasar moderen ketimbang di warung kelontong (Salim, Hawi, dkk. 2014).
Dari survei mini yang diadakan oleh Active Society Institute (AcSI) pada Oktober 2012, menunjukkan bahwa dampak ekspansi mini market baik Alfamart, Indomaret, maupun Alfa Midi terhadap keberadaan warung kelontog mayoritas buruk (70%). Beberapa ragam dampak yang dimaksud meliputi berkurangnya omzet penjualan, khususnya produk tertentu yang sebelumnya diminati seperti minuman segar, minyak goreng, susu formula dan berkurangnya pelanggan karena rayuan harga barang yang lebih murah dan kenyamanan berbelanja yang ditawarkan manajemen minimarket moderen (Salim, Hawi, dkk. 2014).
Hentikan Teror
Serangkain fakta miris itu membukakan mata kita, bahwa teror ekonomi ada di mana-mana. Teror ekonomi terjadi karena negara memberikan ruang maksimal bagi kuasa modal untuk menguasai sumberdaya ekonomi nasional. Sementara kuasa modal berjalan menurut logikanya, yakni maksimalisasi keuntungan. Mereka pun tuna sosial dan tuna budaya. Tidak mengherankan, jika demi pembangunan kawasan industri, pabrik raksasa, perumahan mewah, apartemen, kawasan mewah super blok, dan proyek-proyek mercu suar yang lain, kuasa modal dengan gampangnya mendapatkan izin dan meneror lahan-lahan rakyat.
Ekonomi rakyat yang selama ini sudah berjalan sempoyongan semakin terjepit karena terus menerus mengalami teror mental. Aksesibilitas ke sumberdaya ekonomi pun sangat terbatas. Untuk mengeliminasi tumbuh-kembangnya terorisme ekonomi yang berlangsung secara struktural, maka regulasi dan law enforcement serta pengawasan tegas harus dilakukan. Sementara secara kultural, perlu membangkitkan nasionalisme ekonomi di mana rakyat tahu hak-hak dan kewajibannya sebagai warga.